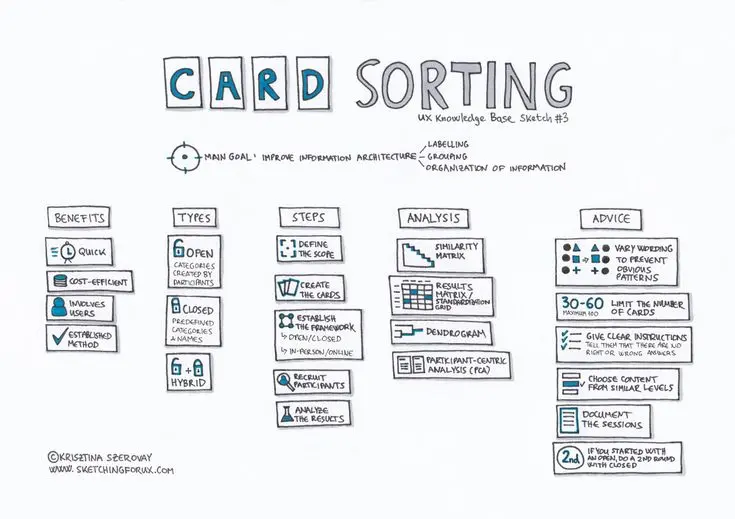Alinea.mmtc – Tindakan Penyitaan buku karya Franz Magnis Suseno, Pramoedya Ananta Toer, dan sejumlah buku judul lain oleh aparat kepolisian usai demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 telah menimbulkan kritik tajam. Bukan hanya soal barang bukti, melainkan tentang batas antara penegakan hukum dan pengekangan pemikiran.

Pada Konferensi pers di Polda RI, buku buku tersebut diperlihatkan sebagai barang bukti kasus kerusuhan anarkisme di sejumlah daerah. Diantaranya “Anarkisme”, “Pemikiran Karl Marx” dan Novel “Anak Semua Bangsa” karya Pramoedya Ananta Toer yang merupakan buku kedua dari series tetralogi baru yang sangat terkenal dan pernah dilarang beredar pada masa orde baru. Kepolisian menyatakan, buku yang turut di perlihatkan adalah bagian dari proses penyelidikan terhadap tersangka demonstran yang di tahan.
Namun, kritik publik dan lembaga HAM tidak kalah keras. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Surabaya, menilai bahwa penyitaan buku adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pemikiran kritis anak muda di indonesia.
Jejak Otoritarian dalam Penyitaan Buku
Mengapa buku dapat dijadikan target ? penyiataan karya intelektual ini mengandung simbolisme yaitu pemikiran yang independen akan dianggap “ancaman”. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menilai tindakan yang dilakukan oleh aparat dengan memamerkan buku sitaan milik demonstran menunjukkan adanya pembungkaman kebebasaran pemikiran di negara demokrasi
Aparat kepolisian masih mengkategorikan buku sebagai barang bukti tindakan kriminal justru menegaskan adanya sisa – sisa mentalitas otoritarian masa orde baru yang masih tertanam di otak dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Pada era pasca reformasi, praktik seperti ini kerap terjadi, antara lain pelarangan dan penyitaan buku yang bertema kiri oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2009, pembubaran diskusi buku Tan Malaka Karya Harry A. Poeze, hingga sweeping buku yang dianggap berbau “Komunisme” di berbagai daerah
Tindakan seperti ini, menunjukkan bahwa Negara Indonesi belum beranjak dari kejadian masa lalu, pola ini menunjukkan bahwa trauma politik masa lalu dijadikan untuk mengekang kebebasan berpikir generasi sekarang.
Tindakan aparat yang menjadikan buku sebagai barang bukti menunjukkan bahwa, lemahnya literasi aparat penegak hukum dalam memahami posisi pengetahuan dan karya sastra serta pembiaran dari pemimpin negara terhadap kecendurungan tindakan represif terhadap sikap kritis dengan dalih keamanan negara. Langkah menyita buku karya intelektual, sudah lama dikenal sebagai bagian dari wacana perlawanan atau kritik sosial dan mengundang pertanyaan.
Antara Hukum dan Kebebasan yang tercekik
Penyitaan buku tak sekedar persoalan hukum, hal ini dapat menyasar nalar masyarakat ketika bacaan yang dipandang “berbahaya” telah disingkirkan, maka ruang diskusi publik menyempit.
Lembaga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingatkan bahwa penyitaan buku mengancam kebebasan berekspresi dan hak masyarakat aas informasi. Operasi penyitaan buku tanpa putusan hukum merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi. Padahal, kedua hal tersebut di jamin dalam pasal 28 E ayat 3 dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“Menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
Penyitaan buku ini mengancam demokrasi Indonesia. Sebab negara yang semestinya memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat justru dirampas oleh aparat kepolisian.
Bentuk Represi Terselubung di Institusi Polri
Langkah menyita buku karya intelektual yang kritis terhadap narasi kekuasaan, bukanlah kebetulan di balik kasus demonstrasi yang terjadi pada tanggal 28 agustus 2025, melainkan ambisi kontrol gagasan. Apabila aparat berhasil membungkam buku, maka suara suara di dalamnya menjadi ancaman.
Demokrasi tak hanya siapa yang duduk di kursi parlemen atau ketika pemilu, melainkan demokrasi sejatinya akan melibatkan ruang berpikir, ruang kritik dan ruang ide yang bebas bertumbuh, termasuk halaman halaman buku.
Negara yang seharusnya menjaga buku agar tetap “alat penerang”, bukan alat pembungkam. Maka dari itu, publik, akademisi, jurnalis dan pembaca harus bersuara : buku tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti kriminal tanpa adanya transparansi hukum.
Penulis : varynnza